
Pendidikan sebagai Investasi Jangka Panjang
Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mempertanyakan apakah gaji guru dan dosen harus sepenuhnya ditanggung negara telah memicu perdebatan luas mengenai tanggung jawab negara dalam pendanaan pendidikan. Pendidikan, sejatinya, merupakan hak publik yang seharusnya dijamin oleh pemerintah. Namun, dalam praktiknya, pendidikan sering kali terjebak pada logika efisiensi, komersialisasi, dan orientasi pasar.
Konstitusi Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 31 UUD 1945, menegaskan bahwa negara wajib mengalokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan. Pada tahun anggaran 2025, alokasi tersebut mencapai senilai Rp724,3 triliun. Selain itu, Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menjelaskan bahwa pendidikan adalah hak warga negara dan kewajiban pemerintah.
Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Namun, dalam prakteknya, idealisme ini sering kali tergerus oleh keterbatasan anggaran, birokrasi yang kaku, serta kebijakan yang kurang berpihak pada kepentingan pendidikan.
Fungsi Pendidikan dan Tantangan Implementasi
Gert Biesta, ahli teori pendidikan dari Belanda, menyebutkan tiga fungsi utama pendidikan, yaitu kualifikasi, sosialisasi, dan subjektifikasi. Kualifikasi merujuk pada pembekalan pengetahuan dan keahlian agar individu dapat berpartisipasi dalam dunia kerja dan masyarakat. Sosialisasi bertujuan untuk mentransmisikan nilai dan norma agar seseorang menjadi bagian dari tatanan sosial. Subjektifikasi membentuk pribadi yang otonom, kritis, dan bertanggung jawab.
Namun, kebijakan sering kali cenderung fokus pada aspek kualifikasi semata, seperti kelulusan, skor ujian, dan penempatan kerja. Hal ini membuat sosialisasi dan subjektifikasi semakin terabaikan. Akibatnya, kurikulum sering kali dipersempit, sehingga aspek non-tes seperti seni dan keterampilan sosial diabaikan. Relasi antara dosen dan mahasiswa pun menjadi lebih transaksional, sementara ruang untuk mengkritisi kebijakan publik semakin sempit.
Antara Pasar dan Pengetahuan
Setiap negara memiliki tiga tipologi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, yaitu sebagai aset nasional, hak publik, atau komoditas. Di negara-negara Nordik seperti Swedia dan Finlandia, pendidikan dipandang sebagai public good yang menjadi hak setiap warga dan sepenuhnya ditanggung oleh negara. Meski prinsip ini tertulis dalam konstitusi, model ini jarang diterapkan di Indonesia.
Sejarah pendidikan tinggi di Indonesia dapat dibagi ke dalam tiga fase besar. Pada masa kolonial, pendidikan dirancang sebagai instrumen kekuasaan, yang memproduksi elit birokrasi yang melayani administrasi penjajah. Setelah kemerdekaan, pendidikan menjadi arena perebutan pengaruh ideologi, khususnya selama era Perang Dingin. Setelah krisis finansial Asia 1997, pendidikan mulai didominasi oleh logika pasar dan komodifikasi.
Di Indonesia, pendidikan tinggi kini sering dianggap sebagai aktivitas pencetak uang. Pemeringkatan kampus menjadi obsesi baru, dengan indikator kuantitatif seperti jumlah publikasi sering kali mengalahkan misi pendidikan itu sendiri. Kompetisi antaruniversitas pun berubah menjadi perlombaan kosong yang menguras sumber daya, sementara orientasi komersial merambah ke banyak aspek, mulai dari kurikulum hingga layanan kampus yang dibungkus seperti produk.
Pendidikan sebagai Investasi, Bukan Pengeluaran
Jika pendidikan terus dipandang hanya sebagai variabel biaya, kita berisiko kehilangan orientasi jangka panjang. Penjaminan pendanaan guru dan dosen bukanlah tindakan amal, tetapi investasi institusional untuk menghasilkan warga negara yang cakap, beretika, dan kritis.
Pengalaman internasional menunjukkan bahwa peran negara dalam pendidikan tinggi tetap krusial, bahkan di sistem yang sangat berorientasi pasar. Meskipun demikian, kontribusi Sri Mulyani melalui pendirian Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) layak diapresiasi karena berhasil memperluas akses beasiswa bagi puluhan ribu pelajar Indonesia.
Partisipasi masyarakat, baik melalui filantropi, dana abadi, maupun kemitraan publik–swasta, bisa menjadi pelengkap yang memperkuat kapasitas negara. Namun, partisipasi ini tidak boleh menggantikan komitmen publik yang telah dijamin konstitusi. Instrumen negara dalam memperluas akses pendidikan tinggi, terutama bagi kalangan menengah ke bawah, perlu dioptimalisasi.
Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibebankan pada masyarakat bisa dinilai sebagai sikap abai negara dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan. Membawa kembali pendidikan pada tiga fungsinya adalah langkah kunci agar kebijakan tidak terjebak pada logika untung-rugi. Dengan keseimbangan yang tepat, pendidikan akan kembali ke hakikatnya: memenuhi amanah konstitusi, memperkuat daya saing, dan membangun peradaban.












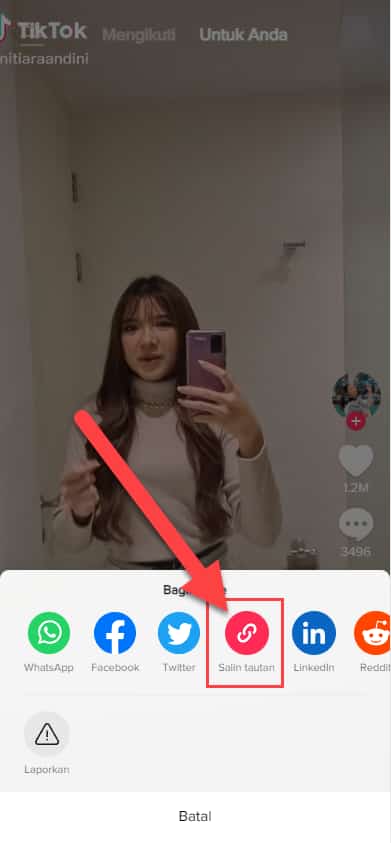








Komentar
Tuliskan Komentar Anda!